Waktu itu aku sedang menempuh pendidikan di sebuah Pondok Pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. Libur awal tahun sebentar lagi akan tiba. Bersama seorang kawan yang berasal dari Palembang aku bersepakat akan pergi ke Bali. Karena bagi santri yang berasal dari luar Pulau Jawa, rugi biaya kiranya jika harus menghabiskan waktu liburan yang hanya sepuluh hari itu di kampung halaman. Apalagi kampong halamanku yang berada nun di sana di pulau terbesar di Indonesia.
Libur awal tahun pun tiba. Rencana mengisi waktu libur di Pulau Bali bersama seorang kawan itu harus pupus terkendala masalah biaya. Sekali lagi aku harus mengubur keinginan menginjakkan kaki di Pulau Dewata itu.
Untuk kesekian kalinya, aku memutuskan untuk menghabiskan waktu liburan yang hanya sepuluh hari ini dengan menyambangi abang kandungku di Yogyakarta.
Jarak antara Ponorogo dan Yogyakarta sekitar kira-kira enam sampai tujuh jam perjalanan dengan bis umum. Kupilih bis. Dengan demikian aku bisa berangkat pagi hari dan sampai di Yogyakarta sore harinya. Aku tak suka naik kereta api, karena harus menyesuaikan waktu keberangkatan mengikuti jadwal. Sedang jadwal kereta api Madiun-Yogyakarta hanya ada di sore hari.
Sekitar jam sembilan pagi aku berangkat. Terlebih dahulu aku harus menunggu angkot untuk mengantarkanku ke terminal Ponorogo. Angkot yang lewat jarang sekali, sehingga cukup menguras waktu. Seringkali ketika ada, sudah penuh dengan warga desa yang membawa barang dagangan yang akan dijual ke kota. Pada hari libur biasa, untuk menghemat waktu, para santri lebih memilih naik ojek atau menyewa sepada. Namun sekarang aku harus sedikit bersabar demi menghemat biaya.
Dari terminal Ponorogo aku harus naik bis lagi menuju terminal Madiun. Dari Madiun aku naik bis jurusan Surabaya-Madiun-Solo-Yogyakarta. Sesampainya di Yogyakarta matahari hampir tenggelam. Aku segera mencari Warung Telepon (Wartel) untuk menghubungi abangku agar dijemput di terminal. Kupencet nomornya. Terdengar suara operator yang mengatakan bahwa nomor yang sedang kutuju tak dapat dihubungi dan menyuruh untuk menghubungi kembali beberapa saat lagi. Kucoba sekali lagi. Masih disambut suara yang sama dari operator, malah sekarang berganti bahasa ke bahasa Inggris. Mungkin operator itu menyangka aku turis asing, pikirku.
Aku mulai was-was. Setengah jam lebih aku mencoba menghubungi abangku. Tapi gagal. Kulihat sisa uang di dompet. Hanya tinggal lima belas ribu. Adzan maghrib mulai berkumandang. Bergegas aku kembali ke terminal sambil berharap masih ada bis kota yang bisa membawaku ke alamat abangku. Hasilnya nihil. Di yogyakarta, batas operasi bis kota hanya sampai jam enam sore.
Tak ada bis kota aku mencari taksi. Kucari supir taksi yang menurut perkiraanku paling baik hati. Kutanya ongkos taksi dari terminal ke daerah Pingit. Supir itu bertanya Pingitnya di mana. Kusebut Jogja Café. Ia membilang dua puluh lima ribu ongkosnya. Aku minta kurang. Ia hanya bersedia mengurangi sebesar lima ribu rupiah. Kembali aku menawar. Ia menolak. Dengan berterus terang kubilang bahwa uangku tinggal lima belas ribu. Ia tetap menolak. Aku pergi dengan hati kecewa.
Kali ini kuputuskan untuk berjalan kaki saja. Rencanaku, aku akan terus berjalan kaki sampai menemukan mesin ATM, setelah menemukan ATM tarik uang lalu naik taksi. Tapi masalahnya aku tak tahu arah. Nekat, aku terus saja berjalan, tak tahu arah, hanya mengikuti ke mana kaki hendak melangkah. Tiba-tiba penyakit magku kambuh. Aku lupa, belum makan sejak pagi tadi. Badanku menjadi sangat lemas. Aku khawatir pingsan di jalan. Untunglah tak lama kemudian aku menemukan warung nasi. Kupesan nasi goreng dan segelas es jeruk. Ketika pesanan tiba nafsu makanku justru menghilang. Apalagi, semakin diisi makanan perutku terasa semakin sakit. Kupaksa terus menyuap. Hanya habis setengah. Hanya minuman yang tersisa es batunya saja. Kubayar pesananku seharga enam ribu rupiah. Kini uangku tersisa sembilan ribu.
Es jeruk yang kuminum sedikit menambah energi. Kulanjutkan perburuan mencari mesin ATM. Setelah sekian lama berjalan, aku sampai pada sebuah simpang empat. Aku bingung akan memilih jalan yang mana. Kuarahkan pandangan sedikit ke atas pada sebuah papan penunjuk jalan. Di sana termaktub kata terminal. Aku kaget. Dan mulai berpikir bahwa selama berjalan tadi aku hanya mutar, dengan kata lain hanya berjalan menuju ke tempat awal berangkat tadi. Aku mulai putus asa.
Saat hampir menyerah, kulihat beberapa tukang becak sedang menunggu penumpang. Tanpa pilih-pilih lagi seperti memilih supir taksi sebelumnya, kuhampiri salah satunya. Aku mendekat kepada seorang tukang becak tua. “Pak, kalau ke ATM BCA terdekat berapa ongkosnya, Pak?” tanyaku
“ATM itu tempat ambil uang, toh?” ia balik bertanya.
“Betul, Pak. Tapi yang BCA. Berapa, Pak?” aku senang mulai menemukan secercah harapan.
“Aduh, jauh e, dek….”
“Iya, Pak, berapa?” desakku semakin penasaran.
“Empat ribu, ya?”
Aku bengong sejenak. Rasa senang, bahagia, kaget, lucu, dan banyak lagi yang lainnya campur-aduk berkecamuk di dadaku. Tadinya kupikir ia akan menawarkan ongkos sampai belasan ribu rupiah, apalagi kata-kata terakhir itu diucapkannya dengan berat sekali dan sedikit rasa tak enak padaku mungkin karena takut kemahalan. Aku segera menganggukkan kepala tanda setuju. Dan berangkatlah aku naik becak menuju mesin ATM.
Bapak tua tukang becak itu terus saja mengayuh becaknya. Dan benar katanya tadi, jarak ke ATM itu sangat jauh. Sesekali ia bertanya tujuanku di Yogyakarta. Kuceritakan semuanya dari awal.
“Yang ini kan, dek?” ujarnya tiba-tiba memotong ceritaku.
Demi membaca tulisan “ATM BCA”, aku melonjak kegirangan. Rasanya bagai seorang anak yang mendapat hadiah mainan baru yang sejak lama diidamkannya.
“Mau ditunggu?” tanyanya kemudian sebelum aku benar-benar turun dari becaknya.
Sekali lagi aku menganggukkan kepala tanda setuju dan bergegas menuju mesin ATM. Setelah mengambil uang kubeli sebungkus rokok, lalu kembali ke Bapak tua tukang becak.
“Mau sekalian diantar ke Pingit, dek?” tanyanya sesampainya aku padanya.
“Wah, boleh, Pak!”
“Tapi tambah tiga ribu, ya? Soale jauh e, dek.”
Sebenarnya mau ditambah lima sampai sepuluh ribu juga, pasti aku akan bersedia. Dalam hati, aku mulai menobatkan ia sebagai pahlawanku. Ya, Dewa Penyelamatku kali ini adalah seorang tukang becak tua. []
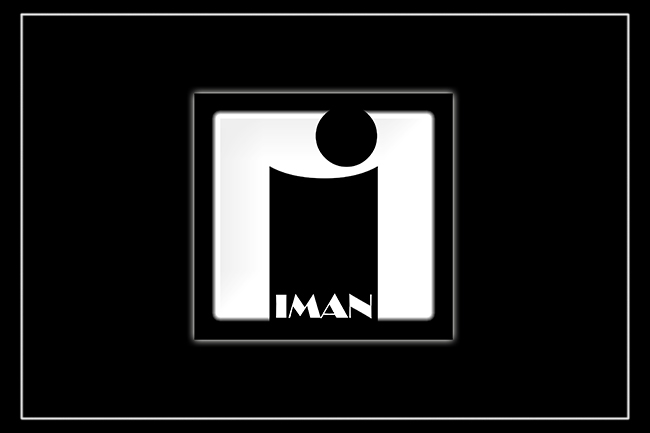
Subhanallah…. semoga kebaikan bapak becak itu mendtangkan rezeki yang banyak bagi keluarga nya dan bermanfaat serta barokah
LikeLiked by 1 person
Amiinnn… YRA
LikeLike
Maaf. … YRA nya lain kali jangan di singkat yh…
LikeLike
Aamiin ya Rabbal’alamin ( آمِيْن يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ )
LikeLike
Alhamdulillah…
LikeLike
Terimakasih…
Alhamdulillah
LikeLiked by 1 person